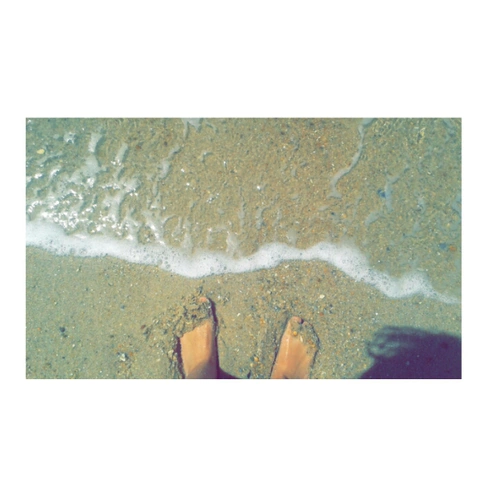Aku melihat tantemu masuk ke halaman rumahmu dengan tergesa-gesa. Anak yang berada di gendongannya seperti sama tidak sabarnya ingin masuk ke dalam rumah dan segera bermain.
Aku terus mengamati dari balik jendela kamar di lantai dua rumahku. Apa kamu tahu? Aku selalu mengamatimu dari sini. Dari kamarku. Padahal untuk menemuimu aku hanya perlu menyeberang jalan, beberapa langkah saja dari rumahku dan aku bisa menatapmu dalam jarak yang sangat dekat.
Tapi aku senang menatapmu dari sini. Aku selalu senang setiap kali aku melihat kamu masuk ke halaman rumahku lalu aku akan segera berlari menuju pintu agar tidak ada yang mendahuluiku membukakan pintu untukmu.
Seperti saat ini juga, aku melihatmu mengantar tante yang datang tadi sampai di depan gerbang rumahmu. Lalu kamu merogoh kantong. Aku segera meraih ponsel yang tergeletak di tempat tidur.
1…2…3…
Drrttt…
Telepon darimu. Jelas. Aku membiarkan ponselku bergetar beberapa saat sebelum mengangkatnya, menikmati debaran jantungku yang memompa tidak karuan mendengar nada dering yang khusus kupakai agar aku bisa mengenali dengan cepat telepon darimu. Aku tidak peduli dadaku terasa agak sakit karena entakan keras di baliknya. Aku senang. Bahagia. Karena ini rasa yang kurasakan padamu. Selalu.
Sudah dua tahun sejak aku mengenalmu tapi aku tidak pernah bisa mengatasi rasa seperti ini jika berada di dekatmu. Responku selalu sama. Deg-degan. Sebentar lagi mungkin aku akan diserang penyakit jantung karenamu.
Ah, aku tidak peduli!
“Ke rumahku, yuk!” katamu saat kuangkat teleponmu. “Butuh bantuan seorang perempuan nih!” Aku tersenyum mendengar suaramu yang memohon, raut wajahmu dari sini juga terlihat jelas. Kamu terlihat lucu.
Kamu terdengar yakin aku pasti akan membantumu. Kamu tidak bertanya apakah aku sedang sibuk?
Benar. Tidak perlu! Karena waktuku selalu ada untuk membantumu. Aku senang merasa dibutuhkan olehmu.
“Tunggu aku di sana!” kataku cepat lalu mematikan telepon. Aku berlari menuruni tangga dan mengatur nafasku yang memburu sebelum membuka pintu rumahku. Tidak lebih dari dua menit aku sudah berdiri di hadapanmu. Kamu tersenyum.
Aku mengikutimu masuk ke dalam rumah yang sepi, ternyata tidak ada orang rupanya, hanya kamu saja. Aku melihat seorang anak laki-laki berumur 3 tahun sedang bermain mobil-mobilan di atas karpet di depan televisi. Ah, ya. Aku ingat. Anak ini yang tadi digendong oleh tantemu. Sepupumu. Pasti dititipkan padamu.
Jadi, kamu memanggilku untuk membantumu menjaga anak ini? Kamu memang sangat tahu kalau aku menyukai anak kecil apalagi yang lucu seperti sepupumu ini.
Apa lagi yang kamu ketahui tentang aku?
Kamu tahu aku suka cokelat!
Kamu tahu aku suka permen susu!
Kamu tahu aku suka pelangi!
Kamu tahu aku tak suka buah pisang!
Kamu tahu aku tak suka wangi minyak kayu putih!
Aku jadi bertanya-tanya, apa yang tidak kamu ketahui tentang aku?
Mungkin kamu tidak tahu kalau aku menyukaimu!
Kamu tak perlu tahu.
Aku ingin rahasia kecil itu milikku sendiri.
Apakah aku sudah mengatakan bahwa sepupu kecilmu ini sangat lucu? Pasti akan seperti kamu jika sudah dewasa nanti. Aku yakin akan banyak gadis-gadis yang menyukainya juga. Seperti kamu.
Tanpa kita sadari hujan sedang mengguyur dengan sangat lebat di luar. Tapi kita tidak peduli, kita berada di dalam rumah yang hangat, aman dan sedang bermain dengan gembira. Bersamamu selalu hangat dan aman. Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu aku khawatirkan?
Lalu sepupumu merengek minta dibuatkan susu, kamu bangkit tanpa mengeluh lalu beranjak menuju dapur. Itu yang aku sangat suka darimu. Kamu terlihat begitu ikhlas ketika mengerjakan sesuatu, tanpa beban, tanpa mengeluh sama sekali. Itu juga sebabnya aku tak pernah bisa menolak jika kamu butuh bantuan. Aku ingin sepertimu. Keikhlasanmu.
Aku mengikutimu menuju dapur. Aku bersandar di pintu dapur dan mengamatimu. Kamu seperti seorang Ayah yang membuat susu untuk anaknya. Senyum tersungging di bibirku kala membayangkan itu. Membayangkan kamu!
Tidak. Tidak. Jangan pedulikan apa yang aku pikirkan! Pikiranku sedang ngelantur. Pikiran warasku tertelan euphoria keindahan yang memanjakan mataku. Kamu lagi!
Aku kembali ke ruang tengah, dan betapa kagetnya aku saat melihat sepupumu sudah tidak lagi berada di tempatnya beberapa menit lalu bermain. Pintu depan terbuka lebar. Aku memekik tertahan. Sepupumu yang ternyata agak bandel itu ada di taman. Bermain air. Basah karena hujan. Aku berusaha memanggilnya tapi dia mengabaikanku. Dia senang bermain lumpur.
Tanpa pikir panjang aku ikut menerjang hujan yang lumayan deras. Aku menggendong sepupumu agar mudah dibawa masuk ke dalam rumah lagi. Aku takut dia bisa sakit. Aku takut kamu marah padaku karena dengan ceroboh meninggalkan sepupumu tanpa pengawasan.
Kamu berdiri menatapku di depan pintu. Segelas susu cokelat hangat tergenggam di tanganmu. Kamu menatapku kaget, takjub, juga kasihan. Kamu kasihan melihatku basah kuyup begini? Jangan. Aku tak suka dikasihani apalagi untuk hal sepele seperti ini. Di depanmu aku selalu ingin terlihat kuat.
Berbasah-basah, aku langsung membawa sepupumu ke kamar mandi untuk memandikannya. Aku merasa tidak enak padamu. Lantai keramikmu yang putih bersih jadi kotor. Basah dan berlumpur.
“Udah, biarin aja lantainya basah. Nanti aku bersihkan!” katamu.
Lalu kamu pergi meninggalkanku yang sedang sibuk dengan sepupumu. Agak lama aku memandikannya karena dia sangat suka bermain air dan dia tidak mau berhenti bermain. Kamu menyodorkan dua buah handuk. Yang berukuran besar untukku dan yang lebih kecil untuk sepupumu. Pakaiannya pun sudah kamu siapkan. Dan pakaianku juga?
“Kamu mandi juga gih, pakaian gantinya udah diambilin tuh!” katamu kasual. Aku takjub.
Aku mengutuki diriku sendiri yang hanya bisa mengangguk saja. Bahkan ucapan terima kasih tak mampu terucap. Kata-kata itu tertelan rasa bahagia. Aku bahagia sekali akan perhatianmu.
Kamu hujan-hujanan ke rumahku hanya untuk mengambilkan pakaian? Pantas saja pakaian dan rambutmu agak basah, itu karena titik hujan rupanya. Kamu pakai payung, kan? Tidak langsung menerjang hujan, kan?
Kamu memang baik sekali. Dan tindakanmu itu juga berarti kamu masih mengizinkanku untuk tetap menemanimu di sini, setidaknya sampai sore nanti.
Lalu kita duduk bersisian di sofa di ruang tengah sambil menonton film kartun. Segelas susu cokelat hangat baru saja kuteguk habis. Lengan kita saling bersentuhan. Lenganmu terasa hangat, tapi lenganku seperti ingin membeku. Sepupumu terkantuk-kantuk di atas pangkuanmu lantas tertidur tidak lama kemudian. Aku sebenarnya juga sangat mengantuk.
“Kita seperti satu keluarga kecil, yah!” Kalimatmu berhasil membuatku terkesima.
Kaget.
Takjub.
Senang.
Melayang.
Berharap!
Aku mencerna kata-katamu. Aku. Kamu. Satu keluarga? Bukankah itu terdengar sangat indah? Pipiku perlahan merona.
Kamu menatapku penuh makna dengan mata hitam yang menghayutkan. Senyum manis tersungging di bibirmu. Aku meleleh.
Aku segera memalingkan muka karena aku tidak berani menatap matamu. Aku takut tersesat di sana. Aku berganti memandangi TV untuk menutupi kegugupan yang tiba-tiba menderaku.
Aku hanya bisa berharap semoga saat kamu mengatakan kalimat itu, malaikat sedang lewat dan mencatat perkataanmu. Bukankah perkataan adalah doa? Dan aku selalu percaya itu!
Aku sudah tidak kuat lagi menahan kantuk hingga aku akhirnya terkulai di bahumu.
Dibuai mimpi tentang kamu.
Tentang kita.
Tentang keindahan.
Memang selalu kamu! ***
2011
Sachakarina